Oleh : Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Para ulama Ahli Hadits berusaha mengumpulkan dan membukukan hadits-hadits lemah dan palsu dengan tujuan agar kaum Muslimin berhati-hati dalam membawakan hadits yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan agar tidak menyebarluaskan hadits-hadits itu hingga orang menyangkanya sebagai sesuatu yang shahih padahal tidak, bahkan ada maudhu’ (palsu). Kendatipun sudah sering dimuat dan dijelaskan tentang kelemahan dan kepalsuan hadits-hadits itu, akan tetapi masih saja kita lihat dan kita dengar para da’i, muballigh, ustadz, ulama, kyai membawakan dan menyampaikan hadits-hadits tersebut, bahkan banyak pula yang ditulis dalam kitab atau majalah, hingga kebanyakan kaum Mus-limin menyangkanya sebagai sabda-sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang benar dan shahih.
Oleh karena itu, saya awali tulisan ini dengan ancaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap orang-orang yang berdusta atas nama beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian diikuti dengan pendapat-pendapat para ulama tentang penggunaan hadits-hadits dha’if.
ANCAMAN BERDUSTA ATAS NAMA RASULULLAH SHALALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
[1] Barangsiapa berdusta atas (nama)ku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari Neraka.”
Hadits ini berderajat MUTAWATIR, karena menurut penyelidikan hadits ini diriwayatkan lebih dari 60 (enam puluh) orang Shahabat ridhwanullahi ‘alaihim jami’an, di antaranya adalah:
1. Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.
2. Anas radhiyallahu ‘anhu.
3. Zubair radhiyallahu ‘anhu.
4. ‘Ali radhiyallahu ‘anhu.
5. Jabir radhiyallahu ‘anhuma.
6. Salman al-Farisi radhiyallahu ‘anhu.
7. Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu dan lainnya.
Dan hadits di atas pun telah dicatat oleh lebih dari 20 (dua puluh) Ahli Hadits, di antaranya: Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Darimy, dan lainnya.
Di antara hadits-hadits tersebut adalah:
[2]. Dari ‘Ali, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah j, ‘Janganlah kamu berdusta atas (nama)ku, karena se-sungguhnya barangsiapa yang berdusta atas namaku, maka pasti ia masuk Neraka.’” [HSR. Ahmad (I/83), al-Bukhari (no. 106), Muslim (I/9) dan at-Tirmidzi (no. 2660)]
[3]. Dari Mughirah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Se-sungguhnya berdusta atas (nama)ku tidaklah sama seperti berdusta atas nama orang lain. Barangsiapa berdusta atas (nama)ku dengan sengaja, maka hendak-lah ia mengambil tempat duduknya dari Neraka.” [ HSR. Al-Bukhari (no. 1291) dan Muslim (I/10), diri-wayatkan pula semakna dengan hadits ini oleh Abu Ya’la (I/414 no. 962), cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah dari Sa’id bin Zaid.)]
Maksud berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam itu ialah: “Membuat-buat omongan atau cerita dengan sengaja yang disandarkan atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ia mengatakan: ‘Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda atau mengerjakan begini dan tidak mengerjakan hal yang demikian.’”
Orang yang berdusta dengan sengaja atas nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam akan masuk api Neraka.
Oleh karena itu, wajib atas kaum Muslimin untuk ber-hati-hati jangan sampai terjatuh dalam dusta atas nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Para ulama telah sepakat tentang haramnya memba-wakan hadits-hadits maudhu’ (palsu), yakni hadits yang dibuat orang atas nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Bolehnya mem-bawakan hadits maudhu’ itu hanya ketika menerangkan kepalsuannya kepada ummat, agar ummat selamat dari berdusta atas nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
HADITS DHAIF (LEMAH)
Hadits dha’if itu ada dua macam:
a. Hadits yang sangat dha’if.
b. Hadits yang tidak terlalu dha’if.
Tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam menolak hadits yang terlalu dha’if. Hanya ada perselisihan di antara ulama tentang membawakan/memakai hadits yang tidak terlalu dha’if untuk:
1. Fadhaa-ilul A’maal (keutamaan amal), maksudnya hadits-hadits yang menerangkan tentang keutamaan- keuta-maan amal.
2. At-Targhiib (memotivasi), yakni hadits-hadits yang berisi pemberian semangat untuk mengerjakan suatu amal dengan janji pahala dan Surga.
3. At-Tarhiib (menakuti), yakni hadits-hadits yang berisi ancaman Neraka dan hal-hal yang mengerikan bagi orang yang mengerjakan suatu perbuatan.
4. Kisah-kisah tentang para Nabi ‘alaihimush Shalatu wa sallam dan orang-orang shalih.
5. Do’a dan dzikir, yaitu hadits-hadits yang berisi lafazh-lafazh do’a dan dzikir.
ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBAWAKAN HADITS DHAIF
Para ulama yang masih membawakan hadits-hadits dha’if dan menyandarkannya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tergolong sebagai pendusta, kecuali apabila mereka tidak tahu.
Tentang masalah ini, Syaikh Abu Syammah berkata: “Perbuatan ulama yang membawakan hadits-hadits dha’if adalah suatu kesalahan yang nyata bagi orang-orang yang mengerti hadits, ulama’-ulama’ ushul dan pakar-pakar fiqih, bahkan wajib atas mereka untuk menerangkannya jika ia mampu. Jika ulama’ tidak mampu menerangkan-nya, maka ia termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sabdanya:
[4]. Dari Samurah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: ‘Barangsiapa yang menyam-paikan hadits dariku, dia tahu bahwa itu dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta.’” [HR. Muslim (I/9).]
Syaikh Abu Syammah berpendapat bahwa tidak boleh menyebutkan suatu hadits dha’if melainkan ia wajib me-nerangkan kelemahannya. [Lihat al-Baits ‘ala Inkari Bida’ wal Hawadits (hal. 54) dan Tamaamul Minnah fiit Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah hal. 32-33.]
Penjelasan:
Menurut hadits di atas seorang dianggap dusta apa-bila ia membawakan hadits-hadits yang diketahuinya dusta (tidak benar).
Ada dua golongan ulama yang terkena ancaman hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas, yaitu: Ulama yang tahu ke-dha’if-an hadits dan yang tidak tahu. Dalam masalah ini ada dua hukum:
Pertama : jika ulama, ustadz atau kyai tersebut tahu tentang lemahnya hadits-hadits yang dibawakan itu, te-tapi ia tidak menerangkan kelemahannya, maka ia ter-masuk pendusta (curang) terhadap kaum Muslimin dan termasuk yang diancam oleh hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas.
Imam Ibnu Hibban berkata: “Di dalam kabar ini (hadits Samurah di atas), ada dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang menyampaikan hadits atau meriwayat-kannya yang tidak sah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu menyampaikan atau meriwayatkan hadits yang lemah atau yang diada-adakan oleh manusia sedang dia tahu bahwa itu dusta, maka dia termasuk pendusta, hal ini lebih keras lagi apabila ulama (ustadz, kyai-pent) tersebut yakin bahwa itu dusta tapi masih disampaikan juga. Hadits ini juga terkena kepada orang yang masih meragukan ke-shahih-an atau kelemahan apa-apa yang ia sampaikan atau riwayatkan.” [Lihat adh-Dhua’faa oleh Ibnu Hibban (I/7-8).]
Imam Ibnu Abdil Hadi menukil perkataan Ibnu Hibban ini dalam kitab ash-Sharimul Mankiy (hal. 165-166) dan beliau menyetujuinya.
Kedua : jika si ulama, ustadz atau kyai tidak mengetahui kelemahan hadits (riwayat), tetapi dia masih menyampai-kan (meriwayatkan) juga, maka dia termasuk orang-orang yang berdosa, karena dia telah berani menisbatkan (me-nyandarkan) hadits atau riwayat kepada Nabi j tanpa ia mengetahui sumber hadits (riwayat) itu.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
[5]. Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Telah bersabda Ra-sulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Cukuplah seo-rang dikatakan berdusta apabila ia menyampaikan tiap-tiap apa yang ia dengar.’” [HSR. Muslim (I/10).]
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mem-punyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung-an jawabnya.” [Al-Israa’: 36]
Imam Ibnu Hibban berkata dalam kitab adh- Dhu’afa’ (I/9): “Di dalam hadits ini (no. 5) ada ancaman bagi se-seorang yang menyampaikan setiap apa yang dia dengar sehingga ia tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa hadits atau riwayat itu shahih.” [Lihat Tamaamul Minnah fii Ta’liq ‘alaa Fiqhis Sunnah hal. 33.]
Imam an-Nawawi pernah berkata: “Bahwa tidak halal berhujjah bagi orang yang mengerti hadits hingga ia tidak tahu, dia harus bertanya kepada orang yang ahli.” [Lihat Qawaaidut Tahdits min Fununi Musthalahil Hadits hal. 115 oleh Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, tahqiq dan ta’liq Muhammad Bahjah al-Baithar]
PENDAPAT BEBERAPA ULAMA TENTANG HADITS-HADITS DHAIF UNTUK FADHAAILUL A'MAAL [KEUTAMAAN AMAL]
Di kalangan ulama, ustadz dan kyai sudah tersebar bahwa hadits-hadits dha’if boleh dipakai untuk fadhaa-ilul a’maal. Mereka menyangka tentang bolehnya itu tidak ada khilaf di antara ulama. Mereka berpegang kepada perka-taan Imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa bolehnya hal itu sudah disepakati oleh ahli ilmu.
Apa yang dinyatakan Imam an-Nawawi rahimahullah tentang adanya kesepakatan ulama yang membolehkan memakai hadits dha’if untuk fadhaa-ilul a’maal ini merupakan satu kekeliruan yang nyata. Sebab, ada ulama yang tidak sepakat dan tidak setuju digunakannya hadits dha’if untuk fadhaa-ilul a’maal. Ada beberapa pakar hadits dan ulama-ulama ahli tahqiq yang berpendapat bahwa hadits dha’if tidak boleh dipakai secara mutlak, baik hal itu dalam masalah ahkam (hukum-hukum) maupun fadha-il.
[a]. Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya, Qawaaidut Tahdits: “Hadits-hadits dha’if tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkaam maupun untuk fadhaa-ilul a’maal, hal ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya, ‘Uyunul Atsar, dari Yahya bin Ma’in dan disebutkan juga di dalam kitab Fat-hul Mughits. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ibnul Araby, Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Hazm. [Qawaaidut Tahdits min Fununi Musthalahil Hadits, hal. 113, tahqiq: Muhammad Bahjah al-Baithar]
[b]. Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany rahimahullah (Ahli Hadits zaman sekarang ini), ia berpendapat: “Pendapat Imam al-Bukhari inilah yang benar dan aku tidak meragukan tentang kebenarannya.” [Tamaamul Minnah fii Ta’liq ‘ala Fiqhis Sunnah hal. 34, cet. Daarur Rayah, th. 1409 H]
Menurut para ulama, hadits dha’if tidak boleh diamalkan, karena:
Pertama.
Hadits dha’if hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah, orang mengamalkan sesuatu dengan prasangka, bukan sesuatu yang pasti diyakini.
Firman Allah:
“Sesungguhnya sangka-sangka itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran.” [Yunus: 36]
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
"AJöauhkanlah dirimu dari sangka-sangka, karena sesungguhnya sangka-sangka itu sedusta-dusta perkataan.” [HR. Al-Bukhari (no. 5143, 6066) dan Muslim (no. 2563) dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu]
Kedua.
Kata-kata fadhaa-ilul a’maal menunjukkan bahwa amal-amal tersebut harus sudah ada nashnya yang shahih. Adapun hadits dha’if itu sekedar penambah semangat (targhib), atau untuk mengancam (tarhiib) dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadits atau riwayat yang shahih.
Ketiga.
Hadits dha’if itu masih meragukan, apakah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam atau bukan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu (menuju) kepada yang tidak meragukan.” [HR. Ahmad (I/200), at-Tirmidzi (no. 2518) dan an-Nasa-i (VIII/327-328), ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul Kabir (no. 2708, 2711), dan at-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.”]
Keempat.
Penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang perkataan Imam Ahmad, “Apabila kami meriwayatkan masalah yang halal dan haram, kami sangat keras (harus hadits yang shahih), tetapi apabila kami meriwayatkan masalah fadhaa-il, targhiib wat tarhiib, kami tasaahul (bermudah-mudah).” Kata Syaikhul Islam: “Maksud perkataan ini bukanlah menyunnahkan suatu amalan dengan hadits dha’if yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena masalah sunnah adalah masalah syar’i, maka yang harus dipakai pun haruslah dalil syar’i. Barangsiapa yang mengabarkan bahwa Allah cinta pada suatu amalan, tetapi dia tidak bawakan dalil syar’i (hadits yang shahih), maka sesungguhnya dia telah mengadakan syari’at yang tidak diizinkan oleh Allah, sebagaimana dia menetapkan hukum wajib dan haram.[ Majmuu’ Fataawaa, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XVIII/65).]
Kelima.
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir menerangkan tentang maksud perkataan Imam Ahmad, Abdurahman bin Mahdi dan ‘Abdullah Ibnul Mubarak tersebut, beliau berkata, “Bahwa yang dimaksud tasaahul (bermudah-mudah) di sini ialah mereka mengambil hadits-hadits hasan yang tidak sampai ke derajat shahih untuk masalah fadhaa-il. Karena istilah untuk membedakan antara hadits shahih dengan hadits hasan belum terkenal pada masa itu. Bahkan kebanyakan dari ulama mutaqadimin (ulama terdahulu) hanyalah membagi derajat hadits itu kepada shahih atau dha’if saja. (Sedang yang dimaksud dha’if itu sebagiannya adalah hadits hasan yang bisa dipakai untuk fadhaa-ilul a’maal-pen). [Baaitsul Hatsits Syarah Ikhtishaar Uluumil Hadiits, oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (hal 87), cet. III Maktabah Daarut Turats, th. 1979 M/1399 H atau cet. I Daarul ‘Ashimah, ta’liq: Syaikh al-Albany]
Sebagai tambahan dan penguat pendapat ulama yang tidak membolehkan dipakainya hadits dha’if untuk fadhaa-ilul a’maal. Saya bawakan pendapat Dr. Subhi Shalih, ia berkata: “Menurut pendapat agama yang tidak diragukan lagi bahwa riwayat lemah tidak mungkin untuk dijadikan sumber dalam masalah ahkam syar’i dan tidak juga untuk fadhilah akhlaq (targhib wat tarhib), karena sesungguhnya zhan atau persangkaan tidak bisa mengalahkan yang haq sedikit pun. Dalam masalah fadhaa'il sama seperti ahkam, ia termasuk pondasi agama yang pokok, dan tidak boleh sama sekali bangunan pondasi ini lemah yang berada di tepi jurang yang dalam. Oleh karena itu, kita tidak bisa selamat bila kita meriwayatkan hadits-hadits dha’if untuk fadhaa-ilul a’maal, meskipun sudah disebutkan syarat-syaratnya.” [ Lihat Uluumul Hadiits wa Musthalaahuhu (hal. 211), oleh Dr. Subhi Shalih, cet. 1982 M]
SYARAT-SYARAT DITERIMANYA HADITS DHA'IF UNTUK FADHAA-ILUL A'MAAL
Di atas sudah saya kemukakan bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Hazm tentang tidak diterimanya hadits dha’if untuk fadhaa-ilul a’maal. Akan tetapi tentunya sejak dulu sampai hari ini masih saja ada ulama yang memakainya. Oleh karena itu, saya bawakan pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany tentang syarat-syarat diterimanya hadits dha’if untuk fadhaa-ilul a’maal, beliau berkata: “Sudah masyhur di kalangan ulama bahwa ada di antara mereka orang-orang yang tasaahul (bermudah-mudah/menggampan
Syaikh Muhammad bin Abdis Salam telah menjelaskan hal ini dan hendaklah seseorang berhati-hati terkena ancaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam (hadits Samurah di atas). Bila sudah ada ancaman ini bagaimana mungkin kita akan mengamalkan hadits dha’if?
Dalam hal ini (ancaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam) terkena bagi orang yang mengamalkan hadits dha’if dalam masalah ahkam (hukum-hukum) ataupun fadhaa-ilul a’maal, karena semua ini termasuk syari’at. [Tabyiinul A’jab (hal. 3-4) dinukil oleh Syaikh al-Albany dalam Tamamul Minnah (hal. 36)]
Al-Hafizh as-Sakhawy, murid al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany t, beliau berkata: “Aku sering mendengar syaikhku (Ibnu Hajar) berkata: “Syarat-syarat bolehnya beramal dengan hadits dha’if:
[1]. Hadits itu tidak sangat lemah. Maksudnya, tidak boleh ada rawi pendusta, atau dituduh berdusta atau hal-hal yang sangat berat kekeliruannya.
[2]. Tidak boleh hadits dha’if jadi pokok, tetapi dia harus berada di bawah nash yang sudah shahih.
[3]. Tidak boleh hadits itu dimasyhurkan, yang akan ber-akibat orang menyandarkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam apa-apa yang tidak beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sabdakan.”
Imam as-Sakhawi berkata: “Syarat-syarat kedua dan ketiga dari Ibnu Abdis Salam dan dari shahabatnya Ibnu Daqiqiil ‘Ied.”
Imam ‘Alaiy berkata: “Syarat pertama sudah disepakati oleh para ulama hadits.” [ Lihat al-Qaulu Badi’ fii Fadhlish Shalah ‘alal Habibisy Syafi’i (hal. 255), oleh al-Hafizh as-Sakhawi, cet. Daarul Bayan Lit Turats]
Bila kita perhatikan syarat pertama saja, maka kewa-jiban bagi ulama dan orang yang mengerti hadits, untuk menjelaskan kepada ummat Islam dua hal yang penting:
Pertama.
Mereka harus dapat membedakan hadits-hadits dha’if dan yang shahih agar orang-orang yang menga-malkannya tidak meyakini bahwa itu shahih, hingga mereka tidak terjatuh ke dalam bahaya dusta atas nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Kedua.
Mereka harus dapat membedakan hadits-hadits yang sangat lemah dengan hadits-hadits yang tidak sangat lemah.
Bagi para ulama, ustadz, dan kyai yang masih bersikeras bertahan untuk tetap memakai hadits-hadits dha’if untuk fadhaaa-ilul a’maal, saya ingin ajukan pertanyaan untuk mereka: “Sanggupkah mereka memenuhi syarat pertama, kedua dan ketiga itu?” Bila tidak, jangan mereka mengamalkannya. Kemudian apa sulitnya bagi mereka untuk mengambil dan membawakan hadits-hadits yang shahih saja yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dan kitab-kitab hadits lainnya. Apalagi sekarang -alhamdulillah- Allah sudah mudahkan adanya kitab-kitab hadits yang sudah dipilah-pilah antara yang shahih dan yang dha’if. Dan kita berusaha untuk memiliki kitab-kitab itu, sehingga dapat membaca, memahami, mengamalkan dan menyampaikan yang benar kepada ummat Islam.
TIDAK BOLEH MENGATAKAN HADITS DHA'IF DENGAN LAFAZH JAZM [LAFAZH YANG MEMASTIKAN ATAU MENETAPKAN]
[a]. Ada (lafazh yang digunakan dalam menyampaikan (meriwayatkan) hadits
menurut pendapat Ibnush Shalah
Apabila orang menyampaikan (meriwayatkan) hadits dha’if, maka tidak boleh anda berkata: “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.”
Atau lafazh jazm yang lain, yakni lafazh yang memastikan atau menetapkan, seperti: "Fa'ala, rawaya, qola".
Boleh membawakan hadits dha’if itu dengan lafazh: “Telah diriwayatkan atau telah sampai kepada kami be-gini dan begitu.”
Demikianlah seterusnya hukum hadits-hadits yang masih diragukan tentang shahih dan dha’ifnya. Tidak boleh kita berkata atau menulis: “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”
[b]. Pendapat Imam an-Nawawi rahimahullah
Telah berkata para ulama ahli tahqiq dari pakar-pakar hadits, “Apabila hadits-hadits itu dha’if tidak boleh kita katakan:
“Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” atau:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengerjakan,” atau:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan,” atau:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang,” atau:
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menghukum.”
Dan lafazh-lafazh lain dari jenis lafazh jazm (pasti atau menetapkan).
Tidak boleh juga mengatakan:
“Telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.” atau:
“Telah menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.”
Dan yang seperti itu dari shighat-shighat (bentuk-bentuk) jazm. Tidak boleh juga menyebutkan riwayat yang lemah dari tabi’in dan orang-orang yang sesudahnya dengan shighat-shighat jazm.
Seharusnya kita mengatakan hadits atau riwayat lemah dan hadits atau riwayat yang tidak kita ketahui derajat-nya dengan perkataan:
"Telah diriwayatkan.
"Telah dinukil darinya.
"Telah disebutkan.
"Telah diceritakan.
Dan yang seperti itu disebut shighat tamridh (bentuk lafazh yang berarti ada penyakitnya), dan tidak boleh dengan shighat jazm.
PERKATAAN PARA ULAMA AHLI HADITS
Shighat jazm seperti: "qola, rawaya"ó dan lainnya hanya digunakan untuk hadits-hadits shahih dan hasan saja. Sedangkan shighat-shighat tamridh, seperti: "ruwiya", atau "dukira"ó dan lainnya digunakan selain itu. Karena shighat jazm berarti menun-jukkan akan sahnya suatu khabar (berita) yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebab itu tidak boleh dimutlakkan.
Jadi, bila ada ulama yang masih menggunakan shighat (lafazh) jazm untuk berita yang belum jelas, berarti ia telah berdusta atas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Adab meriwayatkan ini banyak dilanggar oleh para penulis kitab-kitab fiqh dan juga jumhur Fuqahaa’ dari madzhab Syafi’i, bahkan dilanggar pula oleh jumhur ahli ilmu, kecuali sebagian kecil dari ahli ilmu dari para Ahli Hadits yang mahir.
Perbuatan tasaahul (menggampang-gampangkan) dalam masalah yang hadits merupakan perbuatan yang jelek. Kebanyakan dari mereka menyebutkan hadits shahih dengan shighat tamridh:
“Diriwayatkan darinya.”
Sedangkan dalam menyebutkan hadits dha’if, maka mereka menyebutkan dengan shighat yang jazm: "rawaya fulanun" atau qola".
Hal ini sebenarnya telah menyimpang dari kebenaran yang telah disepakati oleh Ahli Hadits. [Lihat al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzhab, oleh Imam an-Nawawi (I/63), cet. Daarul Fikr.]
WAJIB MENJELASKAN HADITS-HADITS DHAI'F KEPADA UMAT ISLAM
[a]. Perkataan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albany rahimahullah
Ada yang perlu saya tambahkan dari perkataan Imam an-Nawawy di atas tentang penggunaan lafazh tamridh:"ruwiya, yuhkay, dzukira" dan yang seperti itu untuk hadits dha’if.
Zaman sekarang ini penggunaan lafazh-lafazh itu tidak-lah mencukupi, karena ummat Islam banyak yang tidak mengetahui hadits-hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan tidak faham pula kitab-kitab hadits sehu-bungan dengan masalah itu dan tidak mengerti pula apa maksud perkataan khatib di mimbar mengucapkan: “Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”
Bahwa yang dimaksud khatib yaitu hadits itu dha’if, sedangkan mereka banyak yang tidak faham. Maka, wa-jib bagi ulama untuk menjelaskan hal yang demikian itu sebagaimana yang disebutkan oleh Atsar dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata:
“Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa-apa yang mereka ketahui, apakah kamu suka mereka itu dusta atas nama Allah dan Rasul-Nya?!” [HR. Al-Bukhari, Fat-hul Bari (I/225), lihat Shahih Targhib wat Tarhiib (hal. 52), cet. Maktabah al-Ma’arif th. 1421 dan Tamaamul Minnah (hal. 39-40) oleh Syaikh Mu-hammad Nashiruddin al-Albany]
[b]. Perkataan Syaikh Ahmad Muhammad Syakir
Aku berpendapat (sekarang ini) wajib menerangkan hadits-hadits yang dha’if di dalam setiap keadaan (dan setiap waktu), karena bila tidak diterangkan kepada ummat Islam tentang hadits-hadits dha’if, maka orang yang mem-baca kitab (atau mendengarkan) akan menyangka bahwa hadits itu shahih, lebih-lebih bila yang menukilnya atau menyampaikannya itu dari kalangan ulama Ahli Hadits. Hal tersebut karena ummat Islam yang awam menjadikan kitab dan ucapan ulama itu sebagai pegangan bagi mereka. Kita wajib menerangkan hadits-hadits dha’if dan tidak boleh mengamalkannya baik dalam ahkam maupun dalam masalah fadhaa-ilul a’maal dan lain-lainnya. Tidak boleh bagi siapa pun berhujjah (berdalil) melainkan dengan apa-apa yang sah dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam dari hadits-hadits shahih atau hasan. [Lihat al-Ba’itsul Hadits Syarah Ikhtishar ‘Uluumil Hadits oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (hal. 76), cet. Maktabah Daarut Turats th. 1399 H atau I/278, ta’liq: Syaikh Imam al-Albany cet. I Daarul ‘Ashimah th. 1415 H]
AKIBAT TASAAHUL DALAM MERIWAYATKAN HADITS DHAIF
Tasaahul (bermudah-mudah)nya para ulama, ustadz, kyai, dalam menulis dan menyampaikan hadits dha’if tanpa disertai keterangan tentang kelemahannya merupakan faktor penyebab yang terkuat yang mendorong ummat Islam melakukan bid’ah-bid’ah di dalam agama dan ke-banyakan dalam masalah-masalah ibadah. Umumnya ummat Islam menjadikan pokok pegangan mereka dalam masalah ibadah dari hadits-hadits lemah dan bathil bahkan maudhu’ (palsu), seperti melaksanakan shalat dan puasa Raghaa-ib di awal bulan Rajab, malam pertengahan (nisfu Sya’ban), berpuasa di siang harinya, mengadakan perayaan maulud Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Diba’an, baca Barzanji, Yasinan, malam Isra’ Mi’raj dan lain-lain. Akibat tasaahul-nya para ulama, ustadz dan kyai, maka banyak dari ummat Islam yang masih mempertahankan bid’ah-bid’ah itu dan menghidup-hidupkannya. Berarti ada dua bahaya besar yang akan menimpa ummat Islam dengan membawakan hadits-hadits dha’if:
Pertama.
Terkena ancaman berdusta atas nama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, diancam masuk Neraka.
Kedua
Timbulnya bid’ah yang berakibat sesat dan di-ancam masuk Neraka, na’udzubillah min dzaalik.
"Tiap-tiap bid’ah itu sesat dan tiap-tiap kesesatan di Neraka.” [Hadits shahih riwayat an-Nasa-i (III/189), lihat Shahih Sunan Nasa-i (I/346 no. 1487) dan Misykatul Mashaabih (I/51)]
KHATIMAH / PENUTUP
Mudah-mudahan kita terpelihara dari berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dari me-lakukan bid’ah yang telah membuat ummat mundur, terbelakang, berpecah belah dan jauh dari petunjuk al-Qur-an dan Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih. Keadaan seperti merupakan kendala bangkitnya ummat Islam.
Wallaahu a’laam bish Shawaab.
________
MARAAJI’
1. Shahih al-Bukhari.
2. Fat-hul Baari Syarah Shahiihil Bukhary, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar as-Asqalany.
3. Shahih Muslim.
4. Syarah Shahih Muslim, oleh Imam an-Nawawy.
5. Sunan Abi Dawud.
6. Sunan an-Nasa-i.
7. Sunan Ibnu Majah.
8. Jaami’ at-Tirmidzi.
9. Musnad Imam Ahmad.
10. Al-Jarh wat Ta’dil, oleh Ibnu Abi Hatim.
11. Majmu’ Fataawaa, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
12. Manaarul Munif fis Shahih wad Dha’if, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
13. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzhab, oleh Imam Nawawy.
14. Lisanul Mizaan, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany.
15. Al-Qaulul Badi’ fii Fadhilas Shalah ‘ala Habibisy Syafi’i, oleh al-Hafizh as-Sakhawy.
16. Tanzihusy Syari’ah al-Marfu’ah, oleh Ibnu ‘Araq.
17. Ad-Dhu’afa Ibnu Hibban.
18. Qawa’idut Tahdits, oleh Jamaluddin al-Qasimy.
19. Al-Ba’itsul Hatsits fii Ikhtishaari ‘Uluumil Hadiits, oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir.
20. Silsilah Ahaadits ad-Dha’ifah wal Maudhu’ah, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany.
21. Dha’iif Jami’ush Shaghiir, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany.
22. Shahiih Jami’ush Shaghiir oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany.
23. Tamaamul Minnah fii Takhriji Fiqhis Sunnah, oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany.
24. Shahiih at-Targhib wat Tarhiib oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albany.
25. ‘Uluumil Hadits wa Musthalahuhu oleh Dr. Subhi Shalih.
26. Al-Adzkaar, oleh Imam an-Nawawy.
__________________________
[Disalin dari kitab Ar-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Cetakan Pertama Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]




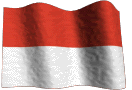


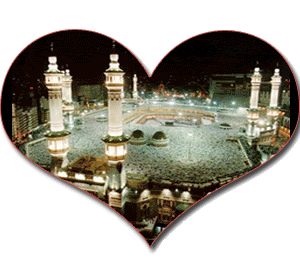















































































































































Tidak ada komentar:
Posting Komentar